Cerpen Emha
KANG DASRIP
Kang
Dasrip kecewa dan agak bingung. Anaknya, Daroji, yang belum sembuh
karena dikhitan kemarin, kini sudah mulai menagih. Sebelum hajat
khitanan ini memang ia sudah berjanji kepada anaknya akan membelikan
radio merek Philip seperti kepunyaan Wak Haji Kholik. Tapi mana bisa.
Perhitungannya ternyata meleset. Ia bukannya mendapat laba dengan hajat
ini, malah rugi. Undangan-undangan itu ternyata banyak yang kurang ajar.
Cobalah
pikir. Perhitungan Kang Dasrip sebenarnya sudah bisa dibilang matang.
Ia keluarkan biaya sesedikit mungkin untuk hajat khitanan anaknya ini.
Ia tidak bikin tarub di depan rumahnya karena akan menghabiskan banyak
batang bambu dan sesek, melainkan cukup dengan membuka gedeg bagian
depan rumahnya. Dengan demikian, beranda dan ruang depan rumahnya
menjadi tersambung dan bisa dijadikan tempat upacara khitanan. Ia tidak
pakai acara macem-macem. Cukup panggil calak, tukang khitan, dengan
bayaran dua ribu rupiah. Kemudian tak usah nanggap wayang atau ketoprak,
ludruk, lagu-lagu dangdut atau kasidahan, atau apa saja asal ada
kasetnya. Semua biayanya cukup tiga ribu rupiah, untuk waktu sehari
semalam penuh.
Biaya
yang tidak bisa dielakkan banyaknya ialah untuk suguhan, makan minum
dan jajan-jajan serta rokok. Yang diundang tak usah banyak-banyak. Cukup
kerabat-kerabat terdekat, tetapi terutama orang-orang yang dulu pernah
mengundangnya berhajat. Kang Dasrip punya catatan berapa banyak ia
memberi beras atau uang ketika ia pergi buwuh ke undangan-undangan dulu
itu. Jadi berdasarkan jumlah buwuhnya itu, pada acara khitanan anaknya
ini, ia yakin pasti memperoleh jumlah yang sama. Bahkan bisa lebih
banyak.
Tetapi
ternyata mereka banyak yang kurang ajar. Yang dulu ia buwuhi Rp 200,-
sekarang cuma ngasih Rp 100,-. Yang dulu ia kasih beras sekilo, sekarang
hanya mbuwuhi setengah kilo. Bahkan ada yang lebih laknat lagi: datang
tanpa bawa apa-apa, padahal ikut makan dan minum. Apa tak kurang ajar.
Kang Dasrip misuh-misuh. Ia rugi ada kira-kira lima belas ribu. Gagallah
ia membelikan radio buat anaknya. Sedang si Daroji sudah
merengek-rengek.
“Sudahlah, Kang. Tak usah bingung. Kita nunggu sewa tebu sawah kita saja untuk beli radio itu, “ kata istri Kang Dasrip.
“Kau
kira berapa sewan untuk sawah kita?” Kang Dasrip malah kelihatan
semakin berang. “Mereka seenaknya sendiri saja memberi harga sewa sawah
kita untuk ditanami tebu. Ngomongnya saja tebu rakyat! Tapi nyatanya
malah maksa-maksa kita, dan tebunya juga punya pabrik! Punya
pemerintah!”
Istrinya tak berani membantah. Tapi Kang Dasrip sendiri toh hanya bisa bingung.
“Biarlah nanti aku yang ngomongi Daroji,“ kata istrinya lagi.
“Ngomongi apa! Dia anak kecil!”
“Ya disuruh sabar.”
Kang Dasrip tertawa kecut. “Sabar sampai kapan?”
“Kita kan bisa usaha.”
“Usaha apa!”
“Soal sewan tebu itu misalnya. Kau kan bisa minta Pak Lurah untuk menaikkan harga sewanya.”
Tertawa
Kang Dasrip mengeras. “Kau kira lurah kita pahlawan, ya! Dia itu takut
sama atasannya. Atasannya itu ada main sama yang ngurus tebu ini. Dan
lagi lurah kita pasti juga dapat apa-apa. Dia sudah punya sawah
berhektar-hektar, pajak-pajak dari kita tak tahu larinya ke mana, uang
pembangunan desa sedikit sekali kita lihat hasilnya, tapi dia belum
pernah merasa puas, dia masih merasa kurang kaya…!”
“Jadi bagaimana?” istrinya tampak sedih.
“Ya bagaimana! Memang bagaimana!” jawab Kang Dasrip.
Mereka kemudian tak berkata-kata lagi.
Tapi
kemudian ternyata Kang Dasrip punya rencana diam-diam. Ia mengambil
sisa-sisa surat undangan, kertas cetakan yang dibelinya di toko dan
tinggal mengisi nama yang diundang. Di bagian belakangnya yang kosong ia
pergunakan untuk menulis surat. Ternyata ditujukan kepada para undangan
yang kurang ajar itu. “Saya dulu mbuwuhi Saudara Rp 200,- kok sekarang
Saudara hanya ngasih Rp 100,-“ tulisnya. “Saya dulu mbuwuhi … kok
sekarang …” demikian ia tulis sampai 23 surat.
Ketika
surat itu selesai diantarnya, ributlah oprang desa. Ada yang tertawa,
ada yang memaki-maki. Yang jelas surat itu dengan cepat menjadi bahan
gunjingan. Bahkan ternyata ada juga yang dikirim ke undangan dari desa
sebelah. Maka makin keraslah tanggapan orang desa. “Memalukan desa
kita!” kecam mereka.
Dan
akhirnya Kang Dasrip memang tidak menikmati hasil apa-apa dari tindakan
kebingungannya itu, kecuali nama yang memalukan. Bahkan lebih dari itu,
di tengah malam ia gelisah karena genting rumahnya ada yang melempari
berkali-kali. Kang Dasrip naik pitam. Ia keluar rumah dan hendak berlari
mengejar pelaku-pelakunya. Tapi tentu saja ini sia-sia. Malam amat
pekat dan lingkungan begitu rimbun untuk ditembus. Akhirnya ia masuk
kembali dan terengah-engah di kursi. Istrinya ketakutan. Tapi Kang
Dasrip berusaha meredakannya. “Mereka-mereka itu undangan kurang ajar!”
katanya.
Paginya
Kang Dasrip berpamitan kepada Daroji akan ke kota untuk beli radio
hingga bersuka citalah anak itu. Tapi siangnya Kang Dasrip datang dengan
wajah sendu. “Radionya dicopet di pasar, Nak …!” ujarnya. Daroji
menanis.
(Emha Ainun Najib dalam Yang Terhormat Nama Saya, Mei 1992)










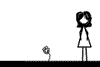


0 komentar:
Posting Komentar